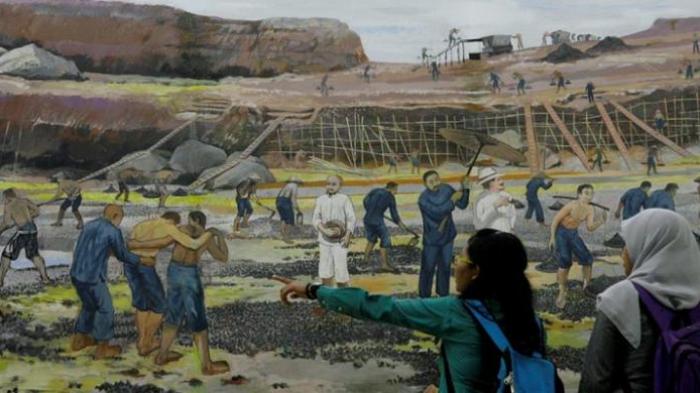KALAU ada satu tempat di Indonesia yang membuat saya sangat ingin mengunjunginya saat ini, maka itu adalah Pulau Flores. Penyebabnya obrolan singkat dengan Mas Sutiknyo, traveler melankolis namun humoris yang lebih dikenal sebagai Tekno Bolang. Cerita Mas Bolang membuat saya begitu terpesona pada Flores, pulau yang disebutnya bakal membuat kita tak ingin mengembara ke tempat lain lagi.
Saya bertemu Mas Bolang di Palembang, dalam rangkaian acara International Musi Triboatton 2016 pada 14-16 Mei lalu. Di hari terakhir pertemuan kami, sembari sarapan di hotel saya berkesempatan mendengar Mas Bolang menceritakan pengembaraannya ke berbagai tempat di Indonesia. Satu destinasi yang membuatnya paling terkesan adalah Flores, tempat yang ia sebut sebagai rumah.
Mas Bolang bercerita, Flores adalah tempat di mana kita bisa sepuasnya menikmati keindahan alam. Dari ujung ke ujungnya bertabur pesona keindahan yang memanjakan mata dan sanubari setiap pengunjung. Demi memuaskan hasrat menikmati setiap sudut Flores, petualang kelahiran Pati ini membawa sepeda motor matic dari kediamannya di Tangerang.
Tentu saja perjalanan tersebut ia abadikan dalam bentuk entah berapa ratus foto dan puluhan video. Saya tanya apakah ia punya channel di YouTube – saya sangat penasaran sekali dengan keindahan Flores yang ia ceritakan. “Cari saja Tekno Bolang,” jawabnya saat itu.
Sepulang dari Palembang saya langsung membuka channel tersebut di YouTube (catatan: nama channel-nya sudah diubah jadi Lostpacker, seusai dengan nama blog dan akun media sosialnya). Tentu saja yang saya cari video-video petualangannya di Flores. Dan saya dibuat terpesona bukan main oleh keindahan alam, juga kearifan budaya lokal yang masih terjaga.
“Saya harus datang ke Flores!” tekat saya dalam hati usai menyaksikan video-video Mas Bolang. Ya, sekalipun hanya sekali seumur hidup saya harus menginjakkan kaki ke Flores.
Tanjung Bunga
Nama Flores sudah saya kenal sejak Sekolah Dasar. Tepatnya setelah mengenal peta, di mana saya begitu lahap mencari informasi mengenai tempat-tempat yang saya lihat dalam atlas. Ketertarikan pada Flores pertama kali timbul ketika Bank Indonesia menerbitkan uang pecahan Rp5.000 bergambar Danau Kelimutu pada tahun 1992.
Saya terpukau oleh cerita Ibu mengenai Danau Kelimutu, danau yang terbentuk dari kawah Gunung Kelimutu. Danau yang menurut cerita Ibu dapat berubah-ubah warna. Terdiri dari tiga kawah yang masing-masingnya menyajikan warna berbeda, karenanya danau ini juga sering disebut sebagai Danau Tiga Warna atau Danau Triwarna.
Sebelum itu saya sudah dibuat tertarik oleh komodo yang terdapat pada koin Rp50. Kadal raksasa yang kata guru saya cuma ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo yang terletak di sebelah barat Pulau Flores. Hewan purba yang konon sudah mendiami Planet Bumi sejak 4 juta tahun lalu.
Tentu bukan tanpa alasan Portugis yang mendarat di nusa ini pada 1512 memberi nama Cabo de Flores, Tanjung Bunga. Nama yang kemudian menggantikan nama asli pemberian penduduk lokal, Nusa Nipa atau Pulau Naga. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda tetap memakai nama Flores ketika mendapatkan wilayah ini dari Portugis 100 tahun kemudian.
Demikian pula dengan Republik Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta, tetap menyebut pulau ini Flores dan memasukkannya dalam Provinsi Sunda Kecil. Sempat berpisah dari RI karena jadi bagian Negara Indonesia Timur, lalu kembali bergabung dengan RI menyusul ambruknya Republik Indonesia Serikat, nama Flores tetap melekat pada pulau satu ini.
Sesuai namanya, Flores adalah sebuah pulau yang menyimpan begitu banyak keindahan dan pesona. Danau Kelimutu di Kabupaten Ende hanyalah salah satunya. Dari video-video yang saya tonton di YouTube, Flores memiliki begitu banyak pantai menawan. Pasirnya putih, dengan ombak tinggi bergulung-gulung dari perairan Laut Sawu dan Laut Flores yang mengelilingi pulau.
Buat pecinta pantai berpasir putih dengan air laut biru kehijauan, kalian wajib datang ke Flores. Selain Pulau Flores, pulau-pulau kecil di sekitarnya juga menyimpan pesona pantai tak kalah mempesona. Tak jauh dari Labuan Bajo ada Pulau Bidadari dengan pantainya yang asri. Atau cobalah ke Pulau Adonara di sebelah timur Flores, di sana ada Pantai Mekko yang sangat memukau.
Bila punya waktu sangat longgar, Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung jadi destinasi yang sangat layak disambangi. Angka 17 tersebut benar-benar mewakili 17 pulau yang ada di sekitaran Teluk Riung. Tempat ini dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama nyaris lima jam dari Labuan Bajo. Namun lelah yang melanda bakal terbayar lunas menyaksikan keindahan pemandangan laut dan pantai berpasir putih bersih yang tersaji di ke-17 pulau.
Ah, saya lupa. Pasir pantai tak selalu berwarna putih. Di Pulau Komodo, kita bisa berjalan-jalan menyusuri sebuah pantai yang pasirnya berwarna merah jambu. Turis mancanegara menyebutnya sebagai Pink Beach, sedangkan penduduk lokal menamainya Pantai Merah. Ya, pasir pantai ini berwarna kemerahan. Hanya ada tujuh pantai di dunia yang pasirnya berwarna merah muda begini.
Sudah sampai di Pulau Komodo, sempatkan waktu untuk mengamati kehidupan hewan langka bernama sama dengan pulau di mana mereka tinggal. Komodo sudah lama jadi perhatian dunia karena keunikannya. Tahun 2011, Pulau Komodo masuk daftar New 7 Wonders of Nature versi New7Wonders Foundation. Lalu tercantum dalam pemenang sementara yang dirilis 11 November 2011.
Meski event garapan New7Wonder Foundation tersebut berbau kontroversi – termasuk penyelenggaranya diragukan, tapi setidaknya menunjukkan bahwa komodo dan Pulau Komodo mendapat perhatian luas di mancanegara. Pesonanya sudah lama memikat wisatawan dari berbagai negara.
Bung Karno dan Secangkir Kopi
Tapi Flores bukan cuma soal pantai indah, laut mempesona, atau komodo yang gagah. Di sini juga tersimpan sejarah bangsa dan negara. Proklamator negeri ini, Bung Karno, pernah tinggal di Flores selama empat tahun sembilan bulan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda membuangnya ke Ende untuk meredam aktivitas politik Sang Proklamator di Batavia.
Ada 10 situs penting terkait pengasingan Bung Karno di Bumi Flores. Di antaranya rumah pengasingan yang terletak di Jl. Perwira. Di rumah inilah Bung Karno menghabiskan kesehariannya dalam masa pembuangan bersama Ibu Inggit Garnasih, anak angkatnya Ratna Djuami, serta ibu mertuanya.
Rumah pengasingan Bung Karno di Ende terawat dengan sangat baik. Kondisinya masih sama persis seperti saat Bung Karno menempatinya dalam rentang waktu 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Berkunjung ke rumah ini kita diajak turut merasakan hari-hari Bung Karno selama menjalani masa pengasingan.
Semasa di Ende inilah Bung Karno melahirkan rumusan Pancasila yang kelak jadi dasar Republik Indonesia. Menurut pengakuannya sendiri saat mengunjungi Ende sebagai Presiden RI pada tahun 1955, Bung Karno menyebut gagasan Pancasila lahir saat ia tengah merenung di bawah sebuah pohon sukun di pusat kota. Tempat dimaksud kini menjadi taman kota bernama Taman Renungan Soekarno, dengan Jl. Soekarno berada di sisinya.
Bung Karno penyuka kopi. Favoritnya kopi tubruk yang biasa ia seruput pagi-pagi di Istana sebelum menjalankan tugas negara. Demikian diceritakan Mangil Martowidjojo, eks Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa yang mendampingi Bung Karno, dalam bukunya berjudul Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967 (Grasindo, 1999).
Sayang, tak ada yang mengungkapkan apakah Bung Karno pernah mencicipi kopi Bajawa atau kopi Wae Rebo semasa tinggal di Flores. Sebab bagi penyuka kopi tak lengkap rasanya mendatangi Flores tanpa mencicipi kopi-kopinya yang khas.
Wae Rebo sebuah kampung tradisional yang terletak di barat daya Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai, NTT. Kampung ini hanya berisi tujuh rumah adat berbentuk kerucut dengan kerangka bambu dan atap dari daun lontar. Orang lokal menyebut rumah ini mbaru niang. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, Waerebo dikelilingi oleh perkebunan kopi nan luas.
Kopi dan Wae Rebo memang tak bisa dipisahkan. Warga Waerebo sangat akrab dengan kopi. Mereka bisa mereguk hingga 8-10 gelas kopi sehari. Tak heran jika banyak penyuka kopi yang sengaja datang ke sini hanya untuk mencicipi kopinya yang khas. Tumbuh di dataran tinggi serta tak tersentuh unsur kimia buatan sedikitpun, cita rasa kopi Wae Rebo banyak disukai oleh pecinta minuman berwarna hitam ini.
Bergeser ke timur, ada Kabupaten Ngada sebagai penghasil kopi terbesar di Flores. Kopi Bajawa hasil panen petani Ngada malah sudah diekspor ke mancanegara. Tahun 2011, seorang pengusaha Amerika Serikat memesan 1.000 ton kopi arabika organik (sumber).
Tak cuma AS, peminat juga datang dari Belanda, Jerman, Inggris, Filipina, dan yang terdekat dari Australia. Masing-masing pesanan berkisar antara 1.000-2.000 ton. Membuktikan betapa kualitas kopi Bajawa telah diakui dunia. So, rugi rasanya kalau ke Flores tak mencicipi kopi Bajawa.
Kearifan Lokal yang Terus Dijaga
Tak jauh dari Bajawa, ada sebuah kampung adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya lokal. Kampung Bena namanya. Masuk ke dalam kampung ini kita serasa mundur ke jaman ratusan tahun lalu. Benar-benar sebuah kampung tradisional.
Terletak di puncak sebuah bukit menghadap Gunung Inerie, Kampung Bena terdiri dari 40 rumah tradisional. Dari kejauhan, Kampung Bena memanjang dari utara ke selatan terlihat seperti bentuk perahu. Pintu masuk berada di sisi utara, satu-satunya akses menuju ke kampung ini. Pada bagian ujung selatan merupakan puncak kampung dengan pemandangan alam mempesona.
Meski memeluk agama Katolik, warga Kampung Bena masih melestarikan tradisi leluhur. Di tengah-tengah Kampung Bena terdapat beberapa bangunan megalitikum. Salah satunya berbentuk perahu, tempat di mana upacara adat dilaksanakan.
Perahu dalam kepercayaan masyarakat Kampung Bena merupakan wahana untuk menuju ke alam roh setelah kematian. Bentuk perahu juga menggambarkan perjalanan nenek moyang penduduk Kampung Bena yang berperahu mengarungi ganasnya lautan dari Pelabuhan Juwana di Pati, Jawa Tengah, sebelum tiba di kampung tersebut.
Pemandangan serupa juga bisa kita saksikan di Ware Rebo. Sebuah perkampungan adat yang masih mengaplikasikan ajaran leluhur dalam kehidupan keseharian. Ciri khas Wae Rebo adalah mbaru niang, rumah adat yang didirikan tanpa paku. Hanya menggunakan bambu, kayu, atau rotan, dengan atap terbuat dari daun lontar, ijuk, atau ilalang.
Di Wae Rebo biasa digelar perayaan Penti, salah satu perayaan besar di Manggarai. Penti digelar setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh selama setahun, sekaligus doa dan harapan agar hasil tahun mendatang tak kalah bagus. Tahun ini, Penti direncanakan berlangsung pada 16 November 2016.
Jika Kampung Bena mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor, tidak demikian dengan Wae Rebo. Pengunjung harus menempuh rute mendaki nan terjal dan sedikit licin berjarak sekitar 5 kilometer. Melintasi Hutan Lindung Todo Repok nan asri, sampai ke ketinggian 1.200 mdpl. Terbayang kan bagaimana sejuknya tempat ini.
*****
Ah, masih sangat banyak pesona Flores yang tidak bisa dilewatkan. Tak cukup waktu 2-3 hari untuk menjelajahinya, karena dari Labuan Bajo di ujung barat hingga Larantuka di ujung timur tersaji keindahan alam yang menawan diselingi kearifan lokal nan menenteramkan sanubari.